
POLITIK UANG MASIH MENGANCAM, PIMPINAN PARPOL JADI AKTOR
Jakarta, MS
Penyakit money politic (politik uang) masih marak menggerogoti pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Indonesia. Ancaman demokrasi itu juga membayangi pesta demokrasi di Sulawesi Utara (Sulut) 2020 ini. Mata kritis publik pun dituntut.
Praktik-praktik politik uang yang masih terjadi dalam Pilkada itu, ikut dikuak Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD.
Ia menyampaikan hal tersebut saat menjadi pembicara pada acara Workshop Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKSI), di Jakarta Barat, Senin (24/2).
Menurut Mahfud, politik uang mulai terjadi sejak zaman Orde Baru. Di masa itu, praktek kotor itu berlangsung di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
"Kalau dulu money politic dalam pemilihan kepala daerah itu ada di DPRD, sekarang berpindah ke pimpinan partai," ujarnya.
Mahfud menyebut di zaman Orde Baru kekuasaan DPRD dianggap buruk karena diberi kekuasaan untuk memilih kepala daerah.
Dengan kekuasaan itu, sering terjadi praktik money politic untuk memilih kepala daerah.
Mahfud mengatakan, politik uang pernah terjadi di Pilkada Yogyakarta dan Jawa Timur pada zaman Orde Baru. Kala itu, anggota DPRD diberi uang untuk meloloskan kepala daerah.
"Mulai di daerah saya di Yogyakarta. Kepala Daerah mau pemilihan, anggota DPRD-nya 45, sebanyak 23 orang dikarantina, dibayar kamu harus pilih ini. Di Jawa Timur juga terjadi demikian. Jadi kemungkinan kepala daerah lalu terjadi jual beli pada waktu itu. Dan itu menjadi bahasan sehari-hari. Kalau begitu kebablasan DPRD yang zaman orde baru itu. Sekarang diperkuat, legislatif menjadi tulang punggung, sekarang menjadi alat jual beli politik untuk jabatan," katanya.
Hanya dengan bermodalkan Rp5 miliar, seseorang bisa menjabat sebagai kepala daerah. Transaksi jual beli jabatan itu bahkan dilakukan secara terang-terangan.
"Itulah untuk jabatan gubernur misalnya waktu itu gampang sekali orang bayar Rp5 miliar satu suara asal memilih gubernur ini. Transaksinya di lobi hotel yang dikontrol oleh ketua fraksi partai," ungkapnya.
Di era Orde Baru peran DPRD hanya dianggap alat pembenar pemerintahan pusat kala itu. Sehingga diubah pada awal era reformasi, DPRD bisa minta pertanggungjawaban dan memberhentikan kepala daerah di tengah jalan, sebagaimana UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
"Tapi demokrasi kemudian dianggap kebablasan. Karena kemudian dalam praktiknya, Ketua atau Kepala Daerah dipilih oleh DPRD, maka pada awal-awal reformasi itu setiap ada Kepala Daerah mulai muncul money politic," beber Mahfud.
Namun, praktik tersebut kini telah berpindah dari DPRD ke partai politik.
"Ndak bayar ke DPRD, bayar ke partai, mahar namanya. Ini terus terang saja, begitu. Apa betul? Ya betul, ya betul lah. Wong sudah dimuat di koran begitu. Orang kan bilang itu tidak ada, tetapi yang kalah itu melapor, yang menang tidak, yang kalah melapor," jelas Mahfud.
Akibat ulah DPRD dengan sistem lama tersebut, yang terkini kena imbasnya. Bahkan melahirkan UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
"DPRD sekarang enggak boleh milih. Satu dia bagian dari pemerintah daerah, yang kedua pemilihan kepala daerah itu langsung, biar enggak ada money politic," tutur Mahfud.
Meski demikian, dia menegaskan, politik uang tidak berhenti.
"Tapi apakah keadaan lebuh baik? Tidak. Kalau dulu money politic dalam pemilihan kepala daerah itu ada di DPRD, sekarang berpindah ke pimpinan partai. Enggak bayar ke DPRD, ke partai. Mahar namanya," ungkap Mahfud.
"Ini terus terang saja, begitu. Apa betul? Ya betul, ya betul lah. Wong sudah dimuat di koran begitu. Orang kan bilang itu tidak ada, tetapi yang kalah itu melapor, yang menang tidak, yang kalah melapor, saya bayar sekian ke Pimpinan Partai," lanjut dia.
Bagi dia, ini adalah ujian politik yang dihadapi sekarang.
"Mari kita sekarang mencari keseimbangan baru. Politik itu begitu, mencari keseimbangan baru," pungkasnya.
POLITIK UANG DIPREDIKSI TETAP MARAK DI 2020
Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menilai persoalan yang terjadi di Pilkada 2020 masih sama dengan Pilkada sebelumnya. Politik uang (money politic) dan permainan isu suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) masih marak.
Akhir tahun lalu, peneliti Perludem, Fadli Ramadhanil memprediksi, selain dua masalah tersebut, aturan regulasi tumpang tindih untuk persyaratan calon kepala daerah diperkirakan masih terjadi di Pilkada tahun 2020.
Kemudian, permasalahan persiapan anggaran serta demokratisasi partai-partai politik dalam mencalonkan para kepala daerahnya.
"Tantangannya secara umum masih sama dengan pilkada-pilkada sebelumnya. Soal persiapan regulasi, persiapan anggaran, dan juga soal demokratisasi parpol dalam pencalonan," ujar Fadli.
Ia juga memprediksi politik uang masih akan marak terjadi di Pilkada 2020. Tak hanya itu, Perludem juga menyoroti integritas dan akuntabilitas dana kampanye para calon kepala daerah.
"Politik uang juga masih jadi soal, termasuk juga integritas dan akuntabilitas dana kampanye," tuturnya.
Kemudian isu SARA diperkirakan masih akan dimainkan dalam Pilkada 2020. Isu SARA dan politik identitas sangat kental terjadi di Pilpres 2019 dan diperkirakan tetap merembet ke Pilkada tahun ini.
Untuk menekan hal itu, maka Fadli meminta agar pihak-pihak terkait di Pilkada 2020 memperhatikan narasi-narasi kampanye di media sosial.
"Konten negatif terhadap narasi kampanye harus lebih positif. Perdebatan kampanye mesti lebih produktif," ucapnya.
MASYARAKAT DIMINTA KRITIS
Penyakit-penyakit lama masih membayangi Pilkada Sulut 2020. Publik pun diminta pintar melihat.
Sorotan pertama mengarahkan ke proses penjaringan calon kepala daerah oleh partai politik (parpol). Publik diminta kritis terhadap para kandidat kepala daerah. Figur yang menggunakan cara-cara tak benar dinilai bukan pemimpin yang baik.
Cacatan itu meletup dari pengamat politik dan pemerintahan Sulut, Ferry Daud Liando. Ia menjelaskan, sekarang ini dalam tahap penjaringan bakal calon kepala daerah (cakada) oleh masing-masing parpol. Proses itu perlu ada peran masyarakat dan media.
Menurutnya, ada parpol yang menggunakan cara-cara yang normatif dan prosedural dalam menjaring calon. Namun ada yang di luar itu dan kurang elok.
“Ada calon yang menetapkan harga-harga tertentu, ada parpol yang menjadikan parpol seperti barang dagangan. Siapa yang mampu membayar lebih tinggi, dia yang dicalonkan. Di satu sisi kalau parpol punya kemampuan walau secara moral kita tidak bisa menerima ada parpol yang membayar calon untuk diusung. Namun setidaknya memperhatikan masalah kapasitas,” tegas Liando.
Sebagian parpol tidak menjadikan kapasitas itu sebagai syarat dalam mengusung calon. Memang diakuinya, jual beli parpol semakin gencar terjadi dan masih berpeluang akan terjadi. “Apalagi ranah Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum) belum sampai ke sana. Ini jadi penting bagi kita untuk ingatkan parpol. Paling tidak yang dicalonkan mempunyai kapasitas dan kemampuan. Ya, yang terjadi kemudian ketika terpilih sulit menjalankan apa yang sudah dijanjikan,” tuturnya.
Ada tiga hal yang dilihatnya sebagai gelagat yang tidak baik dari calon kepala daerah. Itu mengindikasikan mereka nanti bukanlah pemimpin yang baik. “Melihat gelagat dengan memasang baliho dimana-mana. Menaikkan elektabilitas dari popularitas itu penting tapi bukan yang dibuat-buat. Populer itu berdasarkan dedikasi, berdasakan pengabdian kemudian dia populer,” paparnya.
Kemudian gelagat kedua, pemimpin yang tidak baik yakni calon yang membayar parpol. Ketiga, ketika kampanye mengandalkan membayar pemilu untuk dapatkan keuntungan.
“Tiga hal ini memperlihatkan itu bukan pemimpin yang cocok untuk kita. Kita harap itu tidak terjadi lagi. Kalau itu terjadi lagi maka jangan harap pemimpin kita adalah pemimpin yang baik,” tutupnya. (Tim MS/merdeka)






































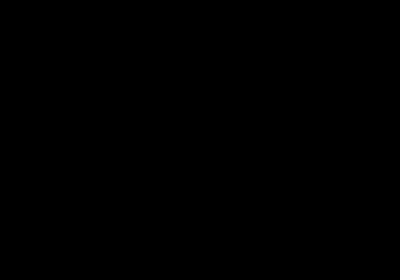
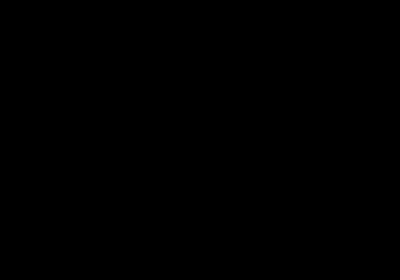
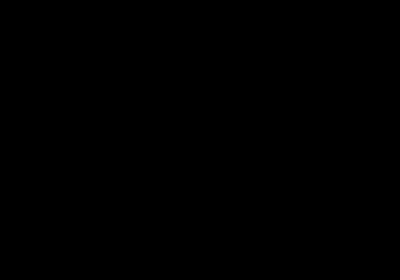
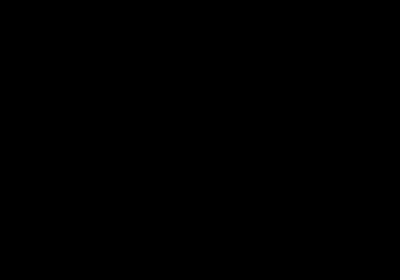






Komentar